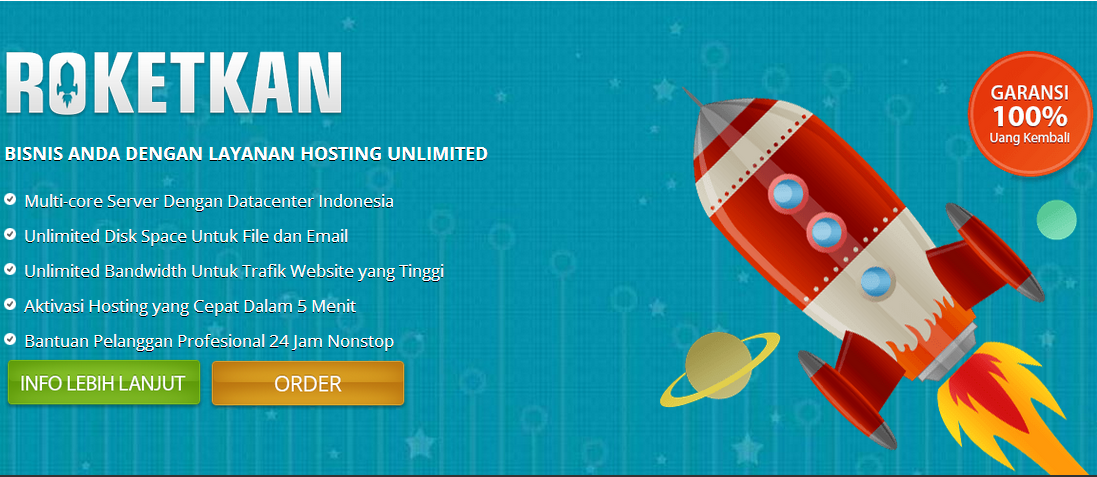Siapa yang tak kenal dengan Brastagi?! Kota kecil di Tanah Karo, Sumatera Utara ini sudah lama akrab dengan kita sebagai salah satu tujuan wisata lokal di Indonesia. Melepas penat dalam kesejukan dataran tinggi sambil memetik buah jeruk di kebun-kebun petani Karo menjadi alasan banyak orang datang ke Brastagi.
Seperti Jakarta yang memiliki tempat peristirahatan di daerah Puncak Bogor, Bali memiliki Kintamani dan Bedugul, Jawa Timur memiliki Batu dan Malang, dan Sumatera Barat memiliki Bukit Tinggi, maka Brastagi menjadi icon Sumatera Utara. Di kota kecil itulah tempat menikmati hijaunya dedaunan dan sejuknya alam perbukitan.
Secara geografis, Brastagi berada di dataran tinggi sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Masuk dalam kawasan Bukit Barisan, dengan diapit dua gunung aktif, Gunung Sibayak dengan ketinggian 2.100 meter dpl dan Gunung Sinabung pada ketinggian 2.400 meter dpl dengan Danau Lau Kawar di kakinya.
Jalanan berkelok-kelok ciri khas Jalur Lintas Sumatera dengan pepohonan khas daerah perbukitan menjadi santapan sepanjang jalan. Brastagi memang berada di kawasan perbukitan. Jalanan sempit dan bergelombang harus dilewati sejauh lebih kurang 60 kilometer dari Kota Medan dengan waktu perjalanan sekitar dua jam.
Infrastruktur Jalan
Sayangnya, potensi Brastagi di bidang pariwisata ini tidak lagi didukung oleh fasilitas umum bagi para pengunjung. Wisatawan tak lagi mendapatkan kenyamanan saat berwisata ke kota kecil ini. Sehingga, berkunjung ke Brastagi pun sama saja menambah penat tubuh.
Infrastruktur jalan Medan-Brastagi belakangan ini terus menjadi sorotan banyak pihak, terutama masyarakat pengguna jalan tersebut. Kenapa tidak, satu-satunya jalan utama paling dekat yang menghubungkan Medan dengan Brastagi itu kondisinya sangat memprihatinkan.
Di beberapa ruas jalan, masih terdapat jalan yang rusak serta tidak rata. Sehingga bisa beresiko membahayakan pengguna jalan. Bahkan, ada bagian jalan yang ambruk akibat longsor hingga memakan setengah badan jalan. Belum lagi banyak badan jalan terus terkikis erosi akibat banjir.
Selain itu, jalannya sempit juga seringkali menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, baik dari Medan maupun yang dari Brastagi. Apalagi pada hari-hari libur atau musim liburan sekolah. Kemacetan yang terjadi bahkan bisa berkilo-kilometer dan terpaksa harus menunggu berjam-jam jika Anda mengendarai mobil.
Akibatnya banyak pengendara sepeda motor yang mengambil jalan di sisi kanan jalan hingga memasuki bagian jalan yang berlawanan arah. Selain beresiko tinggi terhadap pengendaranya karena bisa saja menyebabkan kecelakaan, hal ini juga semakin mempertambah kemacetan yang terjadi.
Belum lagi angkutan umum Medan-Brastagi yang sering ugal-ugalan di jalan raya. Sopir-sopir dari Tanah Batak memang terkenal beringas dan tidak takut mati jika sudah berada di jalanan. Itulah yang akan terlihat di sepanjang jalan, angkutan umum yang ngebut-ngebutan dan saling mendahului untuk mendapatkan penumpang.
Masalah Kebersihan
Ternyata tidak hanya infrastruktur jalan yang tak lagi memadai yang menjadi persoalan, masalah kebersihan juga menjadi sorotan. Saking terbiasanya warga sekitar dengan kondisi ini, lokasi yang jorok dan minimnya fasilitas umum di lokasi objek wisata itu sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah.
Padahal banyak wisatawan yang mengeluhkan hal tersebut. Dimana-mana di sekitar lokasi Bukit Gundaling dan kawasan Pasar Buah yang berada di jantung Kota Brastagi, kotoran kuda yang dijadikan angkutan wisata di daerah tersebut berserakan di sana-sini. Baunya pun menusuk hidung.
Belum lagi sampah yang tiba-tiba merusak pemandangan, teronggok di salah satu sudut taman di Bukit Gundaling. Begitu pun kondisi toilet umumnya jangan ditanya lagi, betapa tidak terurusnya. Padahal, pengunjung sudah membayar retribusi untuk masuk ke lokasi wisata, dan membayar uang kebersihan kamar mandi.
Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, seperti di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kondisinya sangat jauh berbeda. Padahal di kota wisata yang berada di Ranah Minang itu juga terdapat angkutan wisata kuda delman, sama seperti di Brastagi. Namun, pemerintah daerahnya melarang keras adanya kotoran kuda yang berserakan.
Selain itu, juga banyak fasilitas umum lainnya di kawasan taman Bukit Gundaling yang kumuh dan sudah rusak. Terutama beberapa tempat bersantai yang dibangun di tengah-tengah taman yang sudah tak layak lagi di sebuah lokasi wisata. Begitu juga dengan lokasi parkir yang tidak tertata dengan rapi.
Makanya tak heran jika wisatawan yang berkunjung ke Brastagi terus menurun setiap tahun. Bahkan, jika Anda datang ke kota ini, sudah tak banyak lagi turis asing yang bisa dijumpai. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, turis-turis yang berjalan kaki di pusat kota Brastagi sudah menjadi hal yang biasa.
Perhatian Bersama
Persoalan ini tentu saja menjadi permasalahan kita bersama sebagai warga Sumut, demi mengembangkan pariwisata di daerah ini. Jika tidak kita yang melakukan, siapa lagi yang akan peduli dengan negeri kita. Namun, anehnya perhatian pemerintah setempat seakan-akan sudah berkurang, bahkan mulai pudar.
Sebagai salah satu destinasi tujuan wisata, apalagi sudah dikenal di tingkat nasional bahkan hingga ke luar negeri, seharusnya pemerintah daerah memperhatikan hal ini. Misalnya infrastruktur jalan, jika bagus tentunya akan lebih memudahkan akses wisatawan untuk mendatangi Brastagi.
Namun, jika keadaan ini terus dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak akan mungkin Brastagi akan semakin dilupakan orang. Siapa lagi yang mau datang ke Brastagi jika hanya untuk menghabiskan waktu berjam-jam terjebak dalam kemacetan panjang hingga puluhan kilometer?!
* Dimuat di Harian Analisa, Medan (Sabtu, 13 Agustus 2011)
Baca juga di: http://www.analisadaily.com/news/read/2011/08/13/8392/brastagi_riwayatmu_kini/#.TlMmSV0i-So