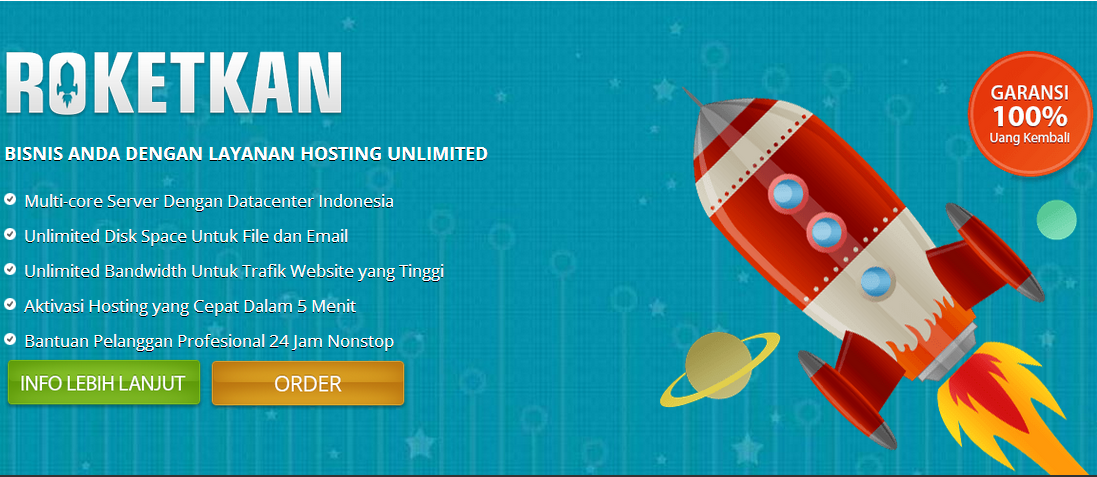Oleh : Adela Eka Putra Marza
"Jangan kalian ‘rusak’ para jurnalis pemula dengan kampanye tolak-amplop. Yang harus dilakukan AJI adalah mendesak semua media agar menggaji wartawannya dengan layak. AJI harus berani menggalang semua wartawan untuk mogok kerja. Setelah itu terpenuhi, barulah ‘sikat’ wartawan yang menerima amplop. Dan sebelum media memberi gaji layak, hentikan kampanye tolak-amplop. Jangan sampai ada (lagi) wartawan yang lugu mengorbankan anak-istrinya demi paham yang kalian ciptakan."
Saya memulai tulisan ini dengan mengutip surat yang ditulis Jarar Siahaan kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dua tahun yang lalu, 28 Maret 2007 di blog-nya (Batak News). Sebuah suara hati dari seorang jurnalis membohongi nuraninya sendiri. Kritikan terhadap cita-citanya sendiri, yang selama ini telah "diperkosa" oleh banyak orang yang munafik. Saya tidak tahu seperti dia menuliskan itu, tapi Saya bisa menangkap kebenaran yang disampaikannya.
Ini bukan hanya soal idealisme semata. Tapi jauh lebih dalam lagi, soal panggilan hati. Seperti yang pernah dikatakan oleh Jakob Oetama, maestro pers Indonesia, "Menjadi wartawan itu adalah panggilan hidup." Jadi bukan untuk bertahan hidup, seperti yang kita lihat selama ini. Makanya tak heran jika pers yang selama ini digadang-gadang menjadi tonggak demokrasi yang keempat, malah menjadi senjata utama untuk menodai demokrasi itu sendiri.
Amplop, Terima Atau Tolak?
Itulah keluhan seorang Jarar Siahaan, yang meminta keadilan di antara idealismenya sebagai seorang wartawan dan kenyataan kehidupan yang akan terus ia jalani. Ia telah belajar banyak tentang ke-idealisme-an dan ke-independen-an seorang wartawan. Namun kenyataan tetap tak berpihak padanya.
Hanya ada dua pilihan yang ia punya - dan mungkin juga hanya dua pilihan ini yang dimiliki oleh banyak wartawan Indonesia - tidak terima "amplop" dengan konsekuensi hidup sekarat karena perusahaan persnya tak memberi upah yang layak, atau terima "amplop" dengan merelakan idealisme dan independennya sebagai seorang wartawan tergadai? Kenyataan yang begitu sulit.
Bukan suatu hal yang aneh lagi jika masih banyak media yang menggaji wartawannya di bawah standar upah minimum. Banyak media nasional yang tak menggaji wartawannya di daerah dengan layak. Sedangkan di daerah, hampir semua media cetak tak menggaji wartawannya dengan layak. Sebagian besar hanya mendapat upah di bawah Rp 1 juta, itu pun hanya bagi wartawan yang bertugas di ibukota provinsi. Sementara yang di daerah-daerah kabupaten, bahkan hampir semua tak digaji.
Melihat kenyataan ini, lalu penjelasan apa yang masih masuk akal bahwa para wartawan tidak akan menerima "amplop"? Pertanyaan itu yang kemudian menjejali otak Jarar Siahaan. Jika tak mengharapkan pendapatan dari "amplop", lalu dari manakah para wartawan akan mendapatkan uang untuk mengisi perutnya dan keluarganya? Tak heran jika banyak wartawan di daerah yang mengandalkan "amplop" dari narasumber untuk biaya hidupnya.
Di setiap media, seperti yang kita tahu, pasti selalu ada sebuah "kalimat keramat" yang mengingatkan "Wartawan kami tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun." Kalimat ini selalu menghiasi box redaksi di media cetak dan disiarkan dalam running text di televisi. Namun bagi para wartawan, "kalimat keramat" itu ternyata tidak lagi menjadi "keramat", karena kita sudah berhadapan dengan masalah perut.
"Tolak amplopnya, ambil isinya", atau "Lihat dulu jumlah angkanya, kalau kecil tolak, kalau besar siapa yang menolak tidak kebagian, lho", menjadi kalimat pamungkas penolak keramat. Saya yakin, Anda para wartawan pasti akan tersenyum kecil - bahkan mungkin tertawa - ketika membaca bagian ini, karena Anda sendiri pasti sudah sangat akrab dengan kalimat-kalimat seperti itu.
Tak hanya pada wartawan, di kalangan narasumber juga ada kalimat-kalimat pamungkas penolak keramat tadi. "Ini sedikit untuk beli minyak", atau "Sekedarnya untuk beli rokok", atau "Kami kan tahu berapa gaji wartawan, ini terima sajalah", itulah kalimat yang sering dibisikkan para narasumber sembari menyelipkan "amplop" di saku celana para wartawan. Ini sudah menjadi rahasia umum, Anda tak usah menyangkal.
Semuanya menggiurkan dan menggoda. Bahkan sering kali nilai nominal dari "amplop" ini lebih besar dari gaji yang didapatkannya dari kantor. Siapa yang mau menolak kalau seperti ini? Pastinya, orang termasuk para wartawan juga butuh hidup, meski idealnya mereka adalah pekerja yang harus berani mengorbankan semuanya demi menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ini soal pilihan hidup. Tapi kedua pilhan tersebut sama beratnya. Ibarat memakan buah simalakama; dimakan ayah mati, tak dimakan emak yang mati. Alamak...! Begitu ironiskah dunia wartawan? Begitulah yang sering terlihat dan semua orang tahu. Jika membicarakan gaji wartawan, sering dianggap tabu apalagi jika menuntut berlebihan ke perusahaan medianya.
Akhirnya, para wartawan yang tak mampu bertahan dengan menggadaikan hati nuraninya seperti itu terpaksa memilih untuk hengkang dari dunia jurnalistik dan memilih profesi lainnya yang dianggap layak dan dapat memberikan penghasilan yang lebih baik. Salah satunya, seperti Jarar Siahaan. Namun pastinya lebih banyak yang bertahan dengan menerima "amplop." Karena mungkin saja mereka sudah merasakan enaknya menikmati "amplop."
Lalu kemudian muncullah istilah-istilah yang tanpa mereka (wartawan) sadari sudah mengdiskreditkan profesi mereka sendiri. Ada yang mengatakan "Wartawan Amplop", "Wartawan Bodrek", "WTS (Wartawan Tanpa Suratkabar)", "Wartawan Ninja", "Wartawan Polisi" dan macam-macam istilah lainnya yang mencoreng citra pers di mata masyarakat. Istilah-istilah yang akhirnya membuat masyarakat mulai meragukan idealisme dan independensi wartawan.
Tuntut Gaji yang Layak
Banyak wartawan dan organisasi kewartawanan yang mengkampanyekan untuk menolak "amplop." Salah satunya adalah AJI yang begitu getolnya menggalang suara anggotanya untuk menolak "amplop" di kalangan wartawan. Bahkan AJI sendiri meng-haramkan-kan anggotanya untuk menerima "amplop" dari narasumber (Saya berharap semua anggota AJI di mana pun di Indonesia ini benar-benar merasa haram untuk menerima "amplop" dari narasumber).
Namun usaha ini jangan hanya setengah-setengah saja, hanya berkoar-koar untuk melarang wartawan menerima "amplop". Sedangkan di belakang, masih banyak wartawan yang diam-diam membuka saku untuk narasumber yang mau menyelipkan "amplop". Kenapa ini masih terjadi? Karena mereka belum mendapatkan upah yang layak dari media tempatnya bekerja. Itulah persoalan utamanya.
Intinya, para wartawan dan organisasi kewartawanan juga harus berani meneriakkan tuntutan kenaikan gaji kepada perusahaan persnya masing-masing. Perusahaan pers harus bisa menjamin kesejahteraan hidup para wartawannya jika kita ingin melihat tak ada lagi "amplop" yang bertebaran setelah acara konferensi pers atau pembukaan suatu kegiatan.
Selain itu, seperti yang pernah disampikan AJI, para wartawan juga harus berserikat dan berorganisasi di perusahaan masing-masing untuk dapat memperjuangkan hak-haknya. Pada kenyataannya, nasib wartawan masih belum secerah yang diharapkan, karena upahnya masih jauh dari layak dibandingkan dengan upah wartawan di luar negeri.
Jika masih ada juga wartawan yang berani menerima "amplop" padahal ia sudah mendapatkan gaji yang layak dari perusahaan medianya, maka sejatinya ia tak pantas menyandang gelar kehormatan "wartawan." Jujur saja, menjadi wartawan itu adalah sebuah kehormatan; sebuah panggilan hidup, bukan tuntutan hidup. Karena ada kekuatan hati nurani dari sebuah kebenaran yang harus disampaikan, itulah yang membuat profesi wartawan berbeda dengan buruh atau pekerja lainnya.
Seperti yang juga disampaikan Jarar Siahaan dalam blog-nya, "Kawan, istriku pernah berkata padaku: "Bukan otak yang membedakan kita dengan binatang, tapi karena kita manusia punya hati nurani." Itulah kawan, kau dan aku masih punya nurani dan rasa malu. Nurani, bukan kejeniusan membeberkan teori-teori dari buku-buku terjemahan yang tebal dan mahal. Karena nurani itulah aku nekat berhenti bekerja di media yang penuh kemunafikan dan perselingkuhan dengan narasumber."
* Dimuat di Harian Analisa (Selasa, 9 Februari 2010)